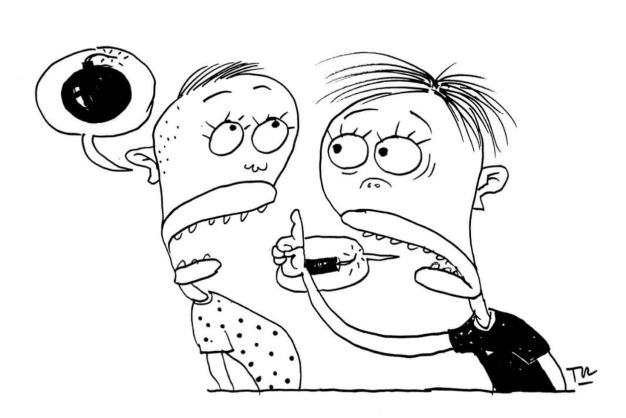Saya masih sibuk mengetik di laptop dengan suara musik mengalun ketika adzan ashar memanggil. Saya beranjak berdiri, mengecilkan suara speaker di meja sudut ruangan. “Sudah azhar”, gumamku. Saya buru-buru menyimpan artikel yang belum selesai, mematikan… More
Saya Belajar Menulis (Lagi)
Tahukah Anda, bahwa awal Januari 2010, saya telah menyandang predikat “mbak-mbak kantoran”? Iya. Maaf. Saya miskin. Saya lulus dengan cepat dan berusaha dengan kecepatan penuh mencari pekerjaan yang gajinya mampu untuk membiayai keluarga dan ibu saya yang janda.
Saya tidak terlahir di keluarga kaya. Almarhum bapak saya hanya PNS dengan pangkat rendahan. Bahkan saat awal kuliah, dimana saya harus merantau hingga beda pulau, Bapak sudah pensiun.
Bagi yang senasib dengan saya, kalian pasti paham cerita selanjutnya.
Pertama, saya harus belajar lebih giat, agar nilai IPK bagus demi beasiswa. Kedua, saya harus bekerja lebih keras, agar dapat uang demi bayar kost – beli buku, baju, sepatu, make up – dan yang paling penting: buat makan sehari-hari.
Diantara reality yang menyayat hati dan ekspektasi hidup meninggalkan kemiskinan itulah, saya memutuskan untuk meng-upgrade diri dengan menciptakan sebuah tujuan hidup: Saya harus segera lulus!
Saya bangun pagi, kuliah, kerja, (kadang) mengerjakan tugas, (kadang) nonton konser, (kadang) nonton teater, (kadang) berkomunitas, pulang, tidur. Berulang-ulang hingga ratusan purnama berlalu.
Setelah melewati begitu banyak drama, saya pun lulus dengan cepat, bonus cum laude. Tak lama kemudian, saya dapat kabar mendapat beasiswa S2, sekaligus diterima bekerja di sebuah instansi pemerintah.
Hidup saya membosankan? Benar. Terdengar biasa-biasa saja? Anda sangat benar.
Meski saya benci sekali menjadi “mbak-mbak kantoran”, di sisi lain itulah awal pertemuan saya dengan Samuel Mulia.
Di tahun-tahun pertama, ruangan tempat saya bekerja jadi satu dengan perpustakaan kantor. Membosankan bagi sebagian Anda, tapi sungguh kemewahan tiada tara bagi saya.
Di tumpukan-tumpukan berdebu itulah saya bertemu banyak buku sejarah, termasuk juga tumpukan artikel Samuel Mulia lewat rubrik “Parodi Urban” di Kompas hari Minggu.
Sebagai generasi kids zaman old, saya masih membaca koran (yang kertasnya membuat tangan berwarna hitam). Bahkan saking cintanya, saya mengkliping banyak artikel-artikel Samuel Mulia. Seaneh itulah saya.
Bertahun-tahun setelah pertemuan pertama itu, saya terobsesi untuk menulis dengan gaya Samuel Mulia. Berhasil? Tentu tidak. Kami punya gaya menulis yang berbeda.
Cara saya menulis adalah tulisan menyayat hati, bukan kritik sosial. Meski di kampus, saya sempat belajar menulis kritik sosial, tapi setelah saya baca lagi, bukan tulisan yang wow banget.
Hingga beberapa hari lalu, berita kematian dari Samuel Mulia membuat saya kembali mengingat diri dan mimpi-mimpi saya di masa lalu.
Mimpi saya, jujur saja, termasuk mimpi yang aneh di negri kita. Di negara yang literasinya nomor dua paling rendah di dunia, bagaimana bisa menulis di sebuah rubrik (meski di salah satu surat kabar terbesar di negri ini) bisa menjadi cita-cita? Cita-cita yang sama sekali tidak membuat kaya, tidak membuat tajir melintir.
Sebagai generasi yang hidup di bawah tekanan sosial bahwa “berhasil” didefinisikan dengan memiliki materi duniawi seperti rumah, mobil, tabungan, liburan ke Luar Negeri, bahkan kalau perlu sudah punya kaplingan makam di salah satu bukit yang biaya sewanya saja sama dengan gaji saya sebulan.
Saya secara sadar menghapus mimpi sebagai penulis rubrik dari list impian saya.
Hingga sebuah pagi, saya bangun dan menuliskan artikel ini. Butuh beberapa jam untuk merampungkan tulisan ini. Saya kehabisan kata-kata, dalih saya. Saya sudah lama tidak menulis dengan gaya seperti ini, mangkir saya.
Saya seperti biasa, memenuhi pagi dengan misuh-misuh pada diri sendiri dan berkata: “Kamu kok sekarang goblok, menulis 500 kata saja butuh berjam-jam”
Artikel ini saya tulis, hapus dan kemudian saya tulis lagi. Tulisan ini bukan agar saya tampak hebat. Ini hanya sebuah pengingat, bahwa 12 tahun yang lalu, saya sempat jadi pribadi yang punya mimpi.
“Saya harus belajar menulis lagi”, kata saya kepada diri sendiri. Dan yang terpenting, saya butuh banyak ruang & waktu bercakap dengan diri sendiri.
Menutup pertemuan pertama ini, mari kita kirimkan Alfatekah untuk Samuel Mulia. Terimakasih telah mengisi masa muda saya dengan tulisan-tulisanmu, Bang.